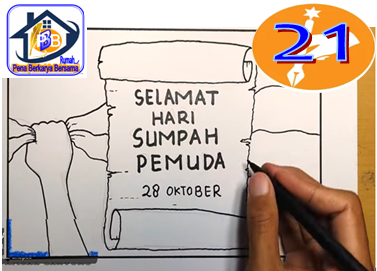
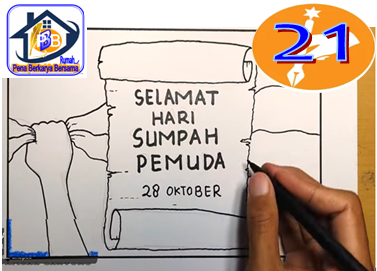
Oleh: A. Rusdiana
Setiap generasi memiliki medan perjuangan. Jika generasi 1928 bersumpah lewat bahasa dan persatuan, maka generasi digital hari ini berjuang lewat tulisan dan narasi. Media sosial, blog, dan portal daring telah menjadi “panggung publik” tempat gagasan dipertarungkan dan nilai-nilai diuji. Namun, di tengah derasnya arus informasi, muncul fenomena baru: tulisan kehilangan akarnya sebagai tanggung jawab sosial. Banyak narasi hanya lahir dari emosi, bukan empati; dari ego, bukan etika.
Teori Social Responsibility of the Press oleh Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi tanggung jawab moral terhadap kebenaran dan kepentingan publik. Dalam konteks akademik, teori ini diperkuat oleh gagasan Ethical Literacy (Bebeau, 2002) yang menempatkan integritas intelektual sebagai bagian dari karakter profesional. Namun, ada gap nyata di kalangan muda: kemampuan menulis berkembang cepat, tetapi kesadaran etis sering tertinggal.
Tulisan ini bertujuan menggugah para anggota komunitas menulis, khususnya PBB (Pelatihan Bahasa dan Budaya), agar melihat menulis sebagai tanggung jawab sosial dan legasi ilmiah, bukan sekadar aktivitas ekspresi pribadi. Melalui refleksi atas tema Hari Sumpah Pemuda 2025 “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu,” penulis mengajak para pemuda menulis untuk berkontribusi dalam merawat persatuan lewat literasi yang beretika, inspiratif, dan ilmiah. Berikut Lima Pembelajaran Mendalam dari “Menulis sebagai Tanggung Jawab Sosial Legasi Ilmiah”:
Pertama: Menulis sebagai Gerak Kolektif, Bukan Aksi Individual; Tulisan seorang pemuda bukanlah miliknya sendiri; ia menjadi bagian dari ekosistem sosial. Ketika satu artikel disebarkan, ia berpotensi membentuk opini publik, bahkan kebijakan. Oleh karena itu, menulis seharusnya dipahami sebagai bentuk collective movement—gerak bersama menuju kesadaran nasional. Pemuda yang menulis berarti turut menggerakkan bangsa untuk berpikir dan bersatu.
Kedua: Etika dan Empati sebagai Fondasi; Tulisan yang baik lahir dari empati sosial. Menurut teori empat etika komunikasi digital (Howard Rheingold, 2012), setiap pesan publik harus memenuhi unsur kejujuran, kejelasan, tanggung jawab, dan kebaikan. Dalam konteks santri atau akademisi muda, etika menulis bukan sekadar menghindari plagiasi, tetapi berani menyuarakan kebenaran dengan santun, menimbang dampak sosial, serta menjaga kehormatan ilmu dan pembacanya.
Keetiga: Literasi Ilmiah sebagai Legasi Peradaban; Legasi ilmiah tidak ditandai oleh viralitas, tetapi oleh validitas. Pemuda perlu menulis dengan dasar riset, teori, dan data agar setiap karya menjadi jejak pengetahuan yang bisa diverifikasi. Di sinilah nilai academic integrity bekerja: menulis berarti membangun warisan intelektual bagi generasi berikutnya, bukan hanya menulis untuk hari ini, melainkan untuk sejarah.
Keempat: Menulis sebagai Medium Persatuan; Semangat Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa bahasa adalah jembatan bangsa. Kini, menulis menjadi jembatan digital yang sama pentingnya. Di tengah polarisasi politik dan perbedaan ideologi, tulisan yang menyejukkan, edukatif, dan inklusif dapat menjadi alat rekonsiliasi sosial. Pemuda penulis adalah peace builder, bukan content fighter. Tugasnya adalah menjaga Indonesia tetap bersatu melalui kata yang beradab.
Kelima: Menulis untuk Transformasi Sosial; Menulis seharusnya berujung pada perubahan sosial. Artikel, esai, atau riset yang baik harus memicu aksi nyata—dari kesadaran menjadi gerakan. Inilah makna sejati Pemuda Bergerak: bukan hanya aktif di media, tetapi memanfaatkan literasi untuk memecahkan masalah bangsa, dari lingkungan, pendidikan, hingga ekonomi kreatif. Dengan menulis, pemuda ikut menyalakan obor peradaban.
Menulis sebagai tanggung jawab sosial berarti menulis dengan niat membangun, bukan menjatuhkan; menulis dengan ilmu, bukan asumsi; dan menulis dengan kasih, bukan amarah. Dalam konteks legasi ilmiah, setiap tulisan pemuda menjadi bagian dari catatan intelektual bangsa yang akan dibaca generasi selanjutnya. Rekomendasi: 1) Bagi lembaga pendidikan, perlu memperkuat pelatihan literasi etis dan akademik digital; 2) Bagi komunitas menulis, dorong kolaborasi lintas kampus dan daerah untuk menghasilkan karya ilmiah populer yang mendidik; 3) Bagi pemerintah dan media, fasilitasi ruang publik yang sehat bagi generasi muda untuk menulis dengan kebebasan yang bertanggung jawab.
Ketika pena pemuda bergerak, sejarah pun bergetar. Menulis adalah bentuk ijtihad sosial usaha intelektual untuk merawat akal sehat bangsa. Di era digital, sumpah pemuda tidak lagi diucapkan lewat podium, melainkan ditulis dengan kesadaran etis di layar. Maka, setiap kali pemuda menulis dengan hati yang bersatu, sejatinya ia sedang melanjutkan sumpah persatuan itu dalam bahasa ilmu dan tanggung jawab sosial. Wallahu A'lam.





![[Pengumuman] Pemenang Lomba Puisi Esai Mini](https://assets.temu.id/imgs/image/2026/02/19/Screenshot_2026-02-19_at_14-58-07_Berdamai_Dengan_Hujan_Air_dan_Keputusasaan_Halaman_all_-_Kompasiana.com.png?t=o&v=243)
![[Pengumuman] Pemenang Lomba Puisi Esai Mini](https://assets.temu.id/userfiles/image/2025/12/31/6a0599ad-68f.png?t=t&v=44)



















